Kiprah Sastrawan Soewarsih Djojopuspito, Perjuangkan Pendidikan bagi Perempuan
11 May 2023 |
13:44 WIB
Kehadiran penyair dan sastrawan perempuan dalam gelanggang kesusastraan Indonesia tidak sebanyak nama-nama sastrawan laki-laki pada awal abad 20. Meski begitu, kehadiran mereka tidak kalah penting untuk dibicarakan, baik dari sisi ketokohan dan kekaryaannya, salah satunya adalah sastrawan Soewarsih Djojopuspito.
Komunitas Salihara dalam program siniar (podcast) rutin Ngomong-Ngomong Soal akan mengangkat topik "Para Perempuan Penulis". Topik ini dimaksudkan untuk mengenal sekaligus menampilkan pentingnya gagasan dan karya penulis perempuan yang namanya barangkali jarang terdengar.
Pada episode perdana, Ibrahim Soetomo sebagai pemandu acara akan berdiskusi dengan narasumber penulis Dhianita Kusuma Pertiwi untuk membahas seputar ketokohan dan kekaryaan Soewarsih Djojopuspito yang dikenal lewat roman “Manusia Bebas” yang terbit pertama kali dalam bahasa Belanda.
Diskusi dibuka dengan mengulas seputar latar belakang keterlibatan Soewarsih dalam pusaran pergerakan nasional. Dhianita menjelaskan bahwa Soewarsih lahir dari lingkungan ningrat dengan ayah yang berprofesi sebagai dalang. Walaupun ayahnya seorang yang buta huruf, dia sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak laki-laki maupun perempuan.
Hal inilah yang membuat Soewarsih dan kakaknya–Nining–sudah disekolahkan di sekolah Belanda seperti Kartini School, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), dan sekolah pendidikan guru di Surabaya. Dalam masa studinya di sekolah pendidikan guru ini, Soewarsih dan Nining menjadi dua Bumiputera dari 28 murid lainnya yang keturunan Belanda.
“Pendidikan itu satu-satunya senjata buat kami untuk menghadapi tantangan masa depan.” bunyi sebuah kutipan dari tulisan yang ditulis Soewarsih dengan kakaknya.
Kutipan tersebut menjadi penanda bahwa sebagai perempuan dan Bumiputera pada masa itu, pendidikan sangatlah diperlukan. Selain itu, keikutsertaan Soewarsih dalam organisasi seperti Jong Java makin memantik kesadaran wanita kelahiran 20 April 1912 ini untuk aktif di dalam pergerakan; terutama untuk menggaungkan pendidikan bagi perempuan Bumiputera dengan aktif mendirikan sekolah-sekolah 'liar'.
Baca juga: Profil Raja Ali Haji, Sastrawan Melayu
Dhianita menjelaskan bahwa kesadaran–untuk aktif dalam pergerakan nasional–tersebut sudah hadir jauh sebelum Soewarsih menikahi suaminya, Sugondo Djojopuspito pada 1933. Menyuarakan emansipasi perempuan memang menjadi fokus utama dalam pergerakan Soewarsih.
Tidak hanya menyuarakan tentang emansipasi, suara vokal Soewarsih juga melebar pada isu-isu lain terutama dalam mengkritik pemerintahan kolonial Belanda, terutama setelah dia menikah dan masuk ke dalam lingkaran tokoh-tokoh nasionalis lainnya.
Soewarsih juga tercatat pernah menulis artikel pada 1941 di sebuah majalah revolusi berjudul Kritiek en Opbouw yang isinya meminta kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengembalikan para tokoh nasionalis yang dibuang ke Boven Digoel, Papua Selatan.
Diskusi ini juga membahas hubungan antara Soewarsih dengan Edgar du Perron, terutama bagaimana du Perron memiliki peran yang besar dalam mendorong Soewarsih untuk menerbitkan karya perdananya yaitu Buiten het Gareel (Manusia Bebas).
Dhianita sebagai narasumber menjabarkan bahwa sebelumnya Soewarsih juga sudah pernah menulis sebuah novel pendek dalam bahasa Sunda yang dikirimkan ke Balai Pustaka namun ditolak akibat penggunaan bahasa yang dinilai rendahan, dan substansi yang subversif yakni mengenai perempuan yang tidak bahagia dalam kehidupan pernikahannya.
Pascapenolakan tersebut, Soewarsih bertemu dengan du Perron dan menceritakan penolakan yang dia terima dari Balai Pustaka. Edgar Du Perron seorang penyair Belanda mendorong Soewarsih untuk kembali menulis namun kali ini menggunakan bahasa Belanda.
Dorongan ini bukan tanpa sebab, Soewarsih yang besar lewat pendidikan yang berbasis bahasa Belanda lebih terbiasa menulis dalam bahasa tersebut. Sebab menurut penuturan Dhianita, bahasa ibu Soewarsih adalah Sunda, dan bahasa Belanda adalah bahasa kedua yang Soewarsih fasih menggunakannya.
Selain menyarankan untuk mengganti penggunaan bahasa, du Perron juga meminta Soewarsih menulis dengan cara yang terbuka, personal, dan langsung sehingga cara penulisan ini dinilai memberikan warna baru dalam kesusastraan Indonesia pada masa tersebut.
Naskah tersebut akhirnya dibawa oleh du Perron ke Belanda dan diterbitkan di Utretch dengan judul Buiten het Gareel di mana du Perron juga menuliskan kata pengantarnya dalam buku tersebut.
Buku ini termasuk ke dalam otobiografi fiksi di mana Soewarsih merepresentasikan dirinya dalam tokoh yang dia namakan Sulastri. Buku ini menampilkan kompleksitas antara ruang publik dan ruang privat di mana Sulastri digambarkan memiliki kompleksitas baik di rumah tangganya, seperti masalah keuangan dan relasi dengan suaminya, Soedarmo, dan kehidupannya di luar sebagai seorang wanita yang aktif dalam kegiatan aktivis dalam mendirikan sekolah-sekolah liar.
Lewat karyanya, Soewarsih ingin memperlihatkan bahwa perjuangan emansipasi tidak hanya dilakukan di ruang publik saja namun juga terjadi dalam skala kecil seperti ruang-ruang privat bahkan termasuk hak dalam menentang poligami. "Karena bagi Soewarsih, pernikahan tidak seharusnya mereduksi peran dan hak perempuan," kata Dhianita.
Novel ini baru bisa dibaca dalam bahasa Indonesia pada 1975 lewat penerbit Djambatan. Dhianita mengakui bahwa penerimaan karya ini tidak semeriah karya bertema nasionalis lainnya yang banyak menggunakan narasi heroik dan maskulin. Soewarsih cenderung banyak menggunakan unsur-unsur privat yang dinilai sepele dan remeh.
Kekuatan Soewarsih dalam menembus batas-batas gender akan peran dan posisi perempuan di masanya juga terlihat di karya-karyanya yang lain. Dhianita menemukan adanya benang mereka antara karya Soewarsih yang dia baca berjudul Marjanah dan kumpulan cerpen Empat Serangkai dengan Manusia Bebas.
Buku-buku tersebut memiliki unsur otobiografis yang menunjukkan perjuangan serta pengangkatan tema yang berani dalam melawan batas-batas gender. Dhianita menilai itu menjadi salah satu langkah berani Soewarsih untuk menggambarkan bagaimana perempuan digambarkan baik dari posisi dan perannya di ranah privat maupun pergerakan.
Menurut Dhianita, Soewarsih menjadi penting untuk dibaca karena melalui karyanya, kita bisa mengetahui bahwa memulai perubahan bisa berawal dari unsur-unsur terkecil seperti ranah privat, tidak harus melalui aksi heroik besar atau berorasi di depan banyak orang.
Baca juga: Momen Penting Kiprah Sastrawan Remy Sylado & Karyanya di Belantika Seni Indonesia
"Soewarsih menyadarkan bahwa untuk menceritakan pergerakan, kita tidak perlu ragu untuk menceritakan diri kita. Karena lewat penyampaian otobiografis tersebut, gagasan yang ingin kita sampaikan akan terasa lebih personal," katanya.
Editor: M R Purboyo
Komunitas Salihara dalam program siniar (podcast) rutin Ngomong-Ngomong Soal akan mengangkat topik "Para Perempuan Penulis". Topik ini dimaksudkan untuk mengenal sekaligus menampilkan pentingnya gagasan dan karya penulis perempuan yang namanya barangkali jarang terdengar.
Pada episode perdana, Ibrahim Soetomo sebagai pemandu acara akan berdiskusi dengan narasumber penulis Dhianita Kusuma Pertiwi untuk membahas seputar ketokohan dan kekaryaan Soewarsih Djojopuspito yang dikenal lewat roman “Manusia Bebas” yang terbit pertama kali dalam bahasa Belanda.
Diskusi dibuka dengan mengulas seputar latar belakang keterlibatan Soewarsih dalam pusaran pergerakan nasional. Dhianita menjelaskan bahwa Soewarsih lahir dari lingkungan ningrat dengan ayah yang berprofesi sebagai dalang. Walaupun ayahnya seorang yang buta huruf, dia sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak laki-laki maupun perempuan.
Hal inilah yang membuat Soewarsih dan kakaknya–Nining–sudah disekolahkan di sekolah Belanda seperti Kartini School, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), dan sekolah pendidikan guru di Surabaya. Dalam masa studinya di sekolah pendidikan guru ini, Soewarsih dan Nining menjadi dua Bumiputera dari 28 murid lainnya yang keturunan Belanda.
“Pendidikan itu satu-satunya senjata buat kami untuk menghadapi tantangan masa depan.” bunyi sebuah kutipan dari tulisan yang ditulis Soewarsih dengan kakaknya.
Kutipan tersebut menjadi penanda bahwa sebagai perempuan dan Bumiputera pada masa itu, pendidikan sangatlah diperlukan. Selain itu, keikutsertaan Soewarsih dalam organisasi seperti Jong Java makin memantik kesadaran wanita kelahiran 20 April 1912 ini untuk aktif di dalam pergerakan; terutama untuk menggaungkan pendidikan bagi perempuan Bumiputera dengan aktif mendirikan sekolah-sekolah 'liar'.
Baca juga: Profil Raja Ali Haji, Sastrawan Melayu
Dhianita menjelaskan bahwa kesadaran–untuk aktif dalam pergerakan nasional–tersebut sudah hadir jauh sebelum Soewarsih menikahi suaminya, Sugondo Djojopuspito pada 1933. Menyuarakan emansipasi perempuan memang menjadi fokus utama dalam pergerakan Soewarsih.
Tidak hanya menyuarakan tentang emansipasi, suara vokal Soewarsih juga melebar pada isu-isu lain terutama dalam mengkritik pemerintahan kolonial Belanda, terutama setelah dia menikah dan masuk ke dalam lingkaran tokoh-tokoh nasionalis lainnya.
Soewarsih juga tercatat pernah menulis artikel pada 1941 di sebuah majalah revolusi berjudul Kritiek en Opbouw yang isinya meminta kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengembalikan para tokoh nasionalis yang dibuang ke Boven Digoel, Papua Selatan.
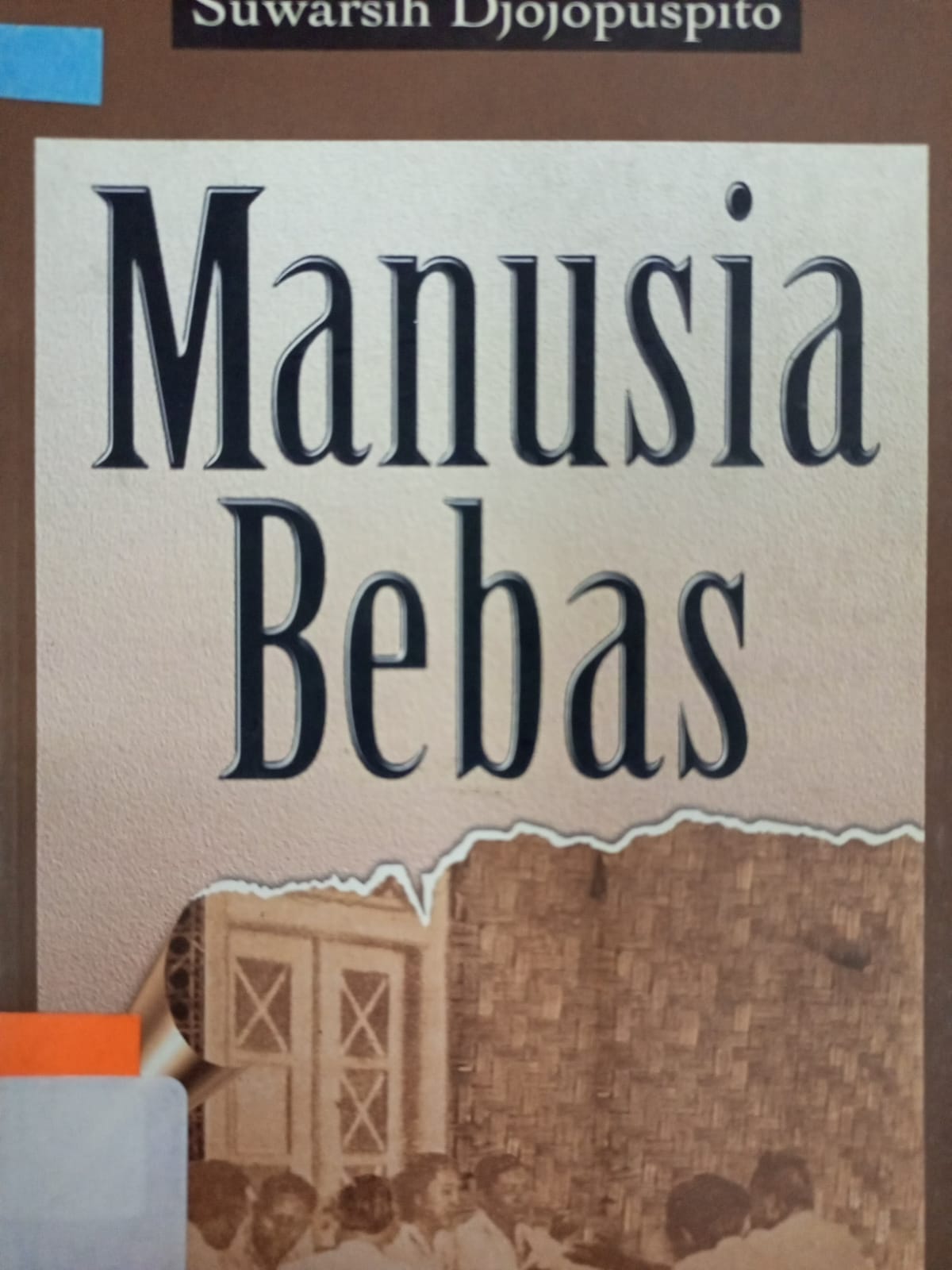
Sumber gambar: Perpusnas RI
Karya Soewarsih di Negara Asing
Diskusi ini juga membahas hubungan antara Soewarsih dengan Edgar du Perron, terutama bagaimana du Perron memiliki peran yang besar dalam mendorong Soewarsih untuk menerbitkan karya perdananya yaitu Buiten het Gareel (Manusia Bebas).Dhianita sebagai narasumber menjabarkan bahwa sebelumnya Soewarsih juga sudah pernah menulis sebuah novel pendek dalam bahasa Sunda yang dikirimkan ke Balai Pustaka namun ditolak akibat penggunaan bahasa yang dinilai rendahan, dan substansi yang subversif yakni mengenai perempuan yang tidak bahagia dalam kehidupan pernikahannya.
Pascapenolakan tersebut, Soewarsih bertemu dengan du Perron dan menceritakan penolakan yang dia terima dari Balai Pustaka. Edgar Du Perron seorang penyair Belanda mendorong Soewarsih untuk kembali menulis namun kali ini menggunakan bahasa Belanda.
Dorongan ini bukan tanpa sebab, Soewarsih yang besar lewat pendidikan yang berbasis bahasa Belanda lebih terbiasa menulis dalam bahasa tersebut. Sebab menurut penuturan Dhianita, bahasa ibu Soewarsih adalah Sunda, dan bahasa Belanda adalah bahasa kedua yang Soewarsih fasih menggunakannya.
Selain menyarankan untuk mengganti penggunaan bahasa, du Perron juga meminta Soewarsih menulis dengan cara yang terbuka, personal, dan langsung sehingga cara penulisan ini dinilai memberikan warna baru dalam kesusastraan Indonesia pada masa tersebut.
Naskah tersebut akhirnya dibawa oleh du Perron ke Belanda dan diterbitkan di Utretch dengan judul Buiten het Gareel di mana du Perron juga menuliskan kata pengantarnya dalam buku tersebut.
Buku ini termasuk ke dalam otobiografi fiksi di mana Soewarsih merepresentasikan dirinya dalam tokoh yang dia namakan Sulastri. Buku ini menampilkan kompleksitas antara ruang publik dan ruang privat di mana Sulastri digambarkan memiliki kompleksitas baik di rumah tangganya, seperti masalah keuangan dan relasi dengan suaminya, Soedarmo, dan kehidupannya di luar sebagai seorang wanita yang aktif dalam kegiatan aktivis dalam mendirikan sekolah-sekolah liar.
Lewat karyanya, Soewarsih ingin memperlihatkan bahwa perjuangan emansipasi tidak hanya dilakukan di ruang publik saja namun juga terjadi dalam skala kecil seperti ruang-ruang privat bahkan termasuk hak dalam menentang poligami. "Karena bagi Soewarsih, pernikahan tidak seharusnya mereduksi peran dan hak perempuan," kata Dhianita.
Perjuangan Novel Manusia Bebas di Indonesia
Meski novel Buiten het Gareel atau Manusia Bebas memiliki pesan pergerakan yang kuat, buku tersebut harus menemui jalan terjal dalam proses menemui para pembacanya. Mulai dari awal terbitnya pada 1940 yang tidak bisa didistribusikan di Indonesia akibat situasi perang, bahkan saat cetak ulangnya pada 1946 akibat agresi militer yang terjadi di Tanah Air.Novel ini baru bisa dibaca dalam bahasa Indonesia pada 1975 lewat penerbit Djambatan. Dhianita mengakui bahwa penerimaan karya ini tidak semeriah karya bertema nasionalis lainnya yang banyak menggunakan narasi heroik dan maskulin. Soewarsih cenderung banyak menggunakan unsur-unsur privat yang dinilai sepele dan remeh.
Kekuatan Soewarsih dalam menembus batas-batas gender akan peran dan posisi perempuan di masanya juga terlihat di karya-karyanya yang lain. Dhianita menemukan adanya benang mereka antara karya Soewarsih yang dia baca berjudul Marjanah dan kumpulan cerpen Empat Serangkai dengan Manusia Bebas.
Buku-buku tersebut memiliki unsur otobiografis yang menunjukkan perjuangan serta pengangkatan tema yang berani dalam melawan batas-batas gender. Dhianita menilai itu menjadi salah satu langkah berani Soewarsih untuk menggambarkan bagaimana perempuan digambarkan baik dari posisi dan perannya di ranah privat maupun pergerakan.
Menurut Dhianita, Soewarsih menjadi penting untuk dibaca karena melalui karyanya, kita bisa mengetahui bahwa memulai perubahan bisa berawal dari unsur-unsur terkecil seperti ranah privat, tidak harus melalui aksi heroik besar atau berorasi di depan banyak orang.
Baca juga: Momen Penting Kiprah Sastrawan Remy Sylado & Karyanya di Belantika Seni Indonesia
"Soewarsih menyadarkan bahwa untuk menceritakan pergerakan, kita tidak perlu ragu untuk menceritakan diri kita. Karena lewat penyampaian otobiografis tersebut, gagasan yang ingin kita sampaikan akan terasa lebih personal," katanya.
Editor: M R Purboyo










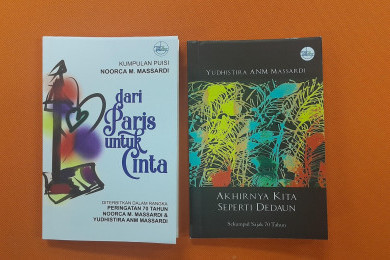
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.